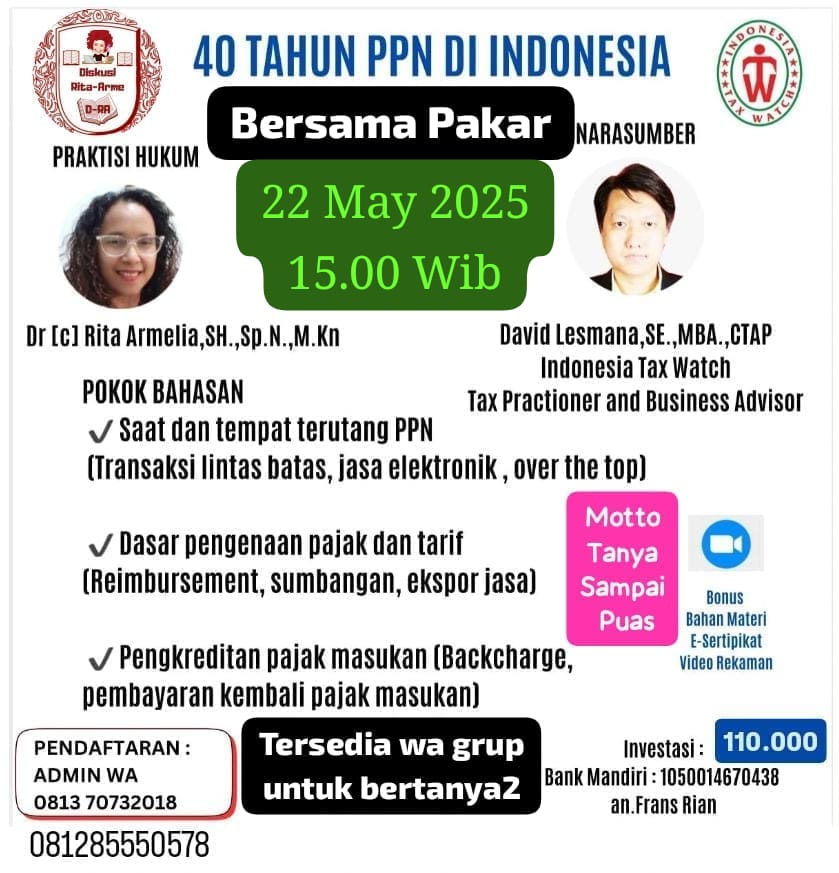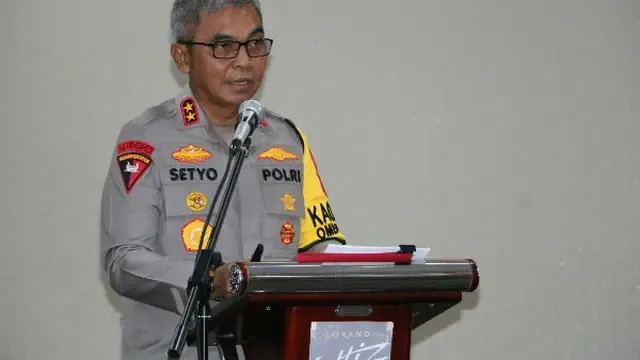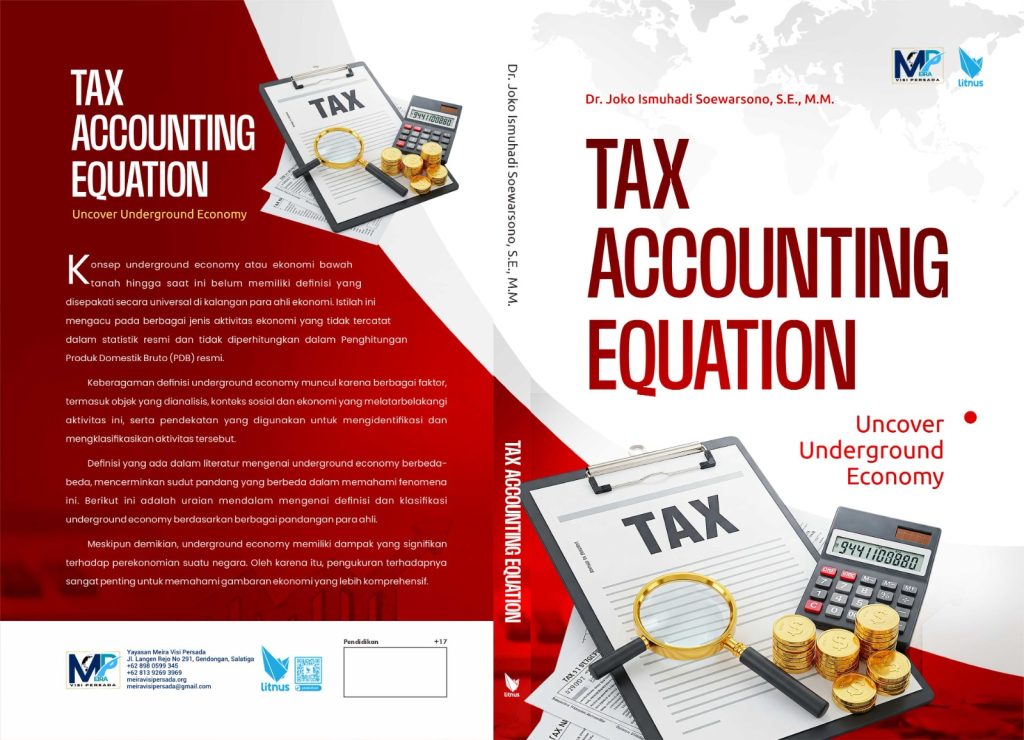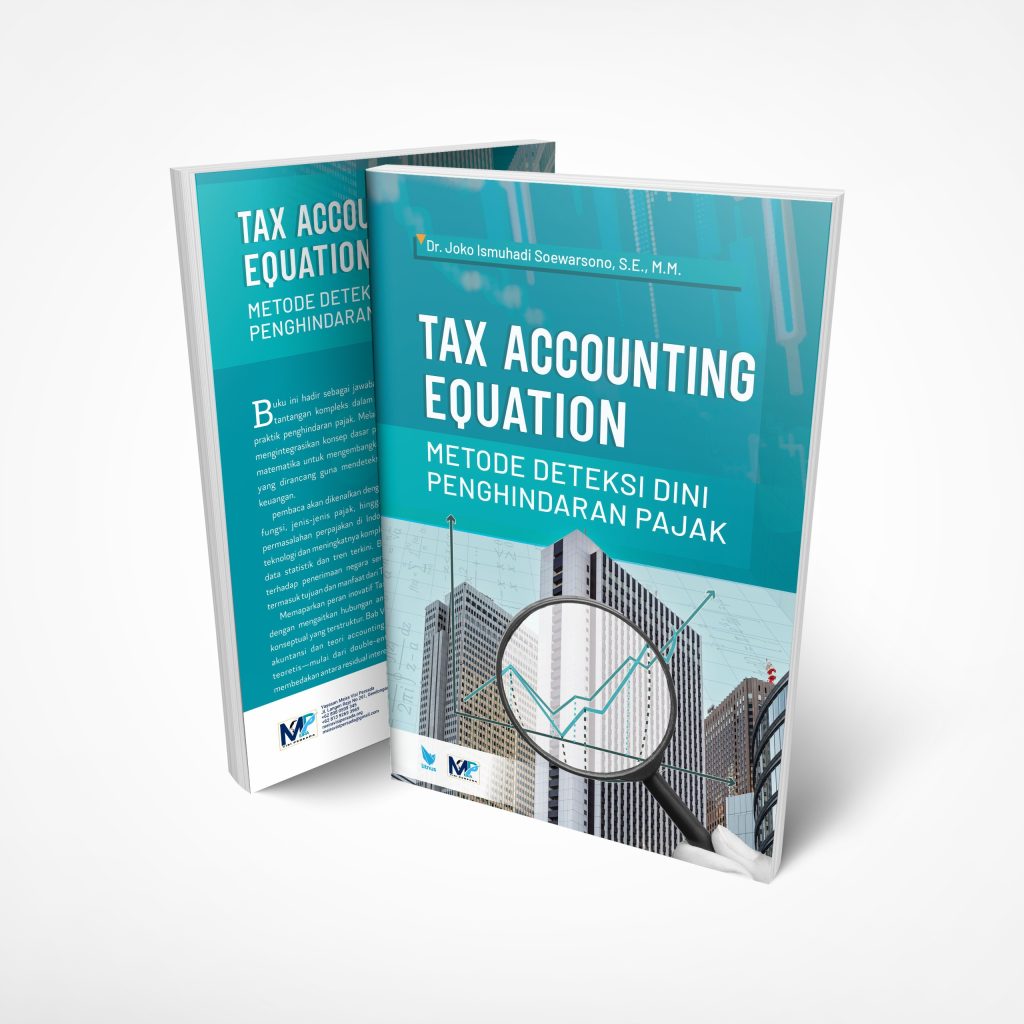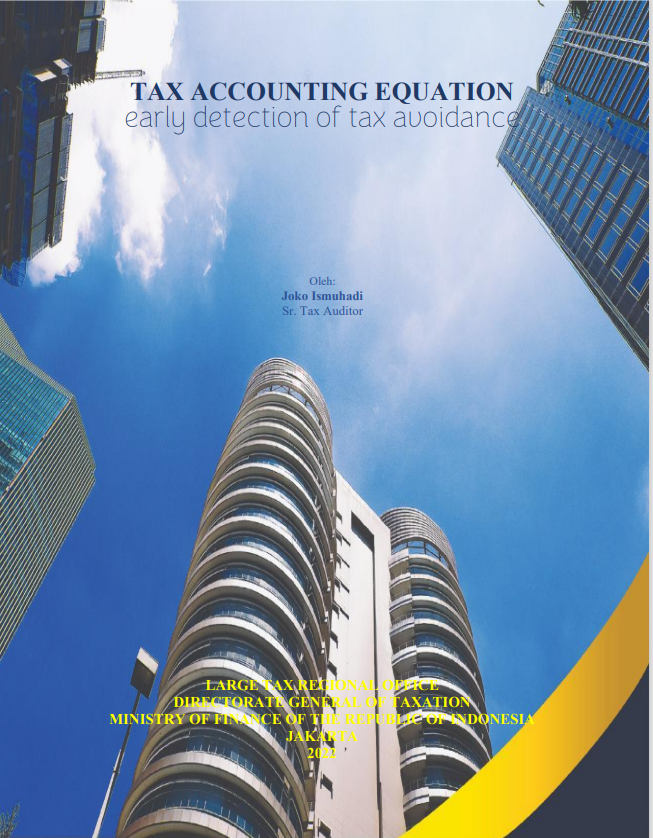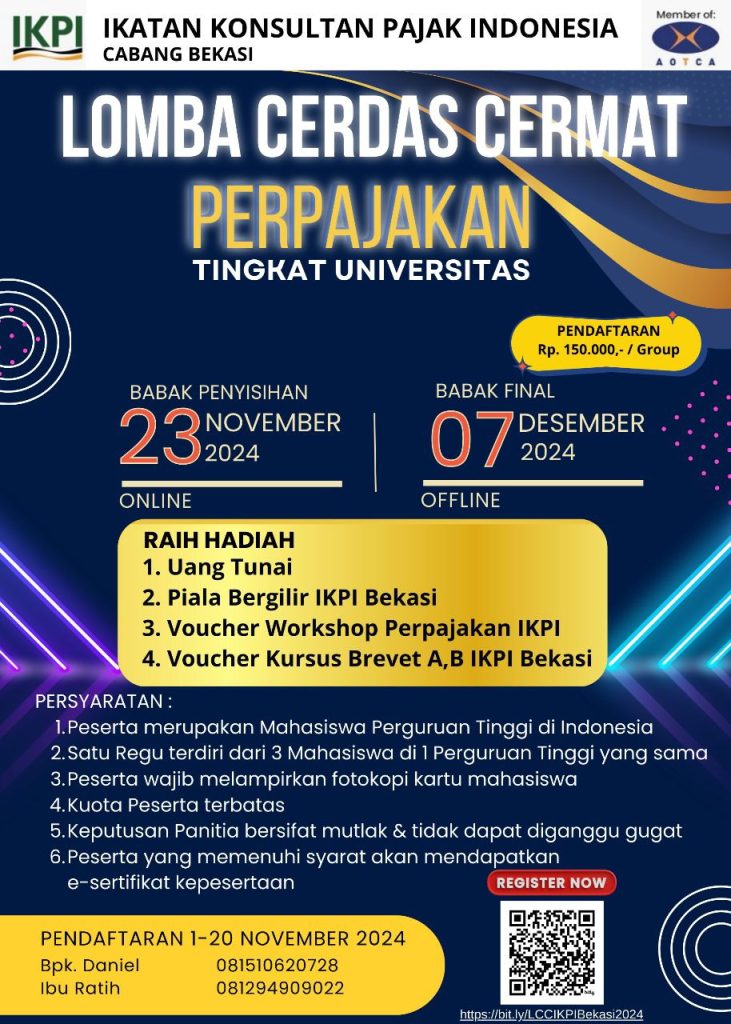Irisan Tindak Pidana Perpajakan dan Korupsi di Indonesia: Telaah Penerapan Keadilan Restoratif
- Ekonomi
Friday, 16 May 2025 23:30 WIB
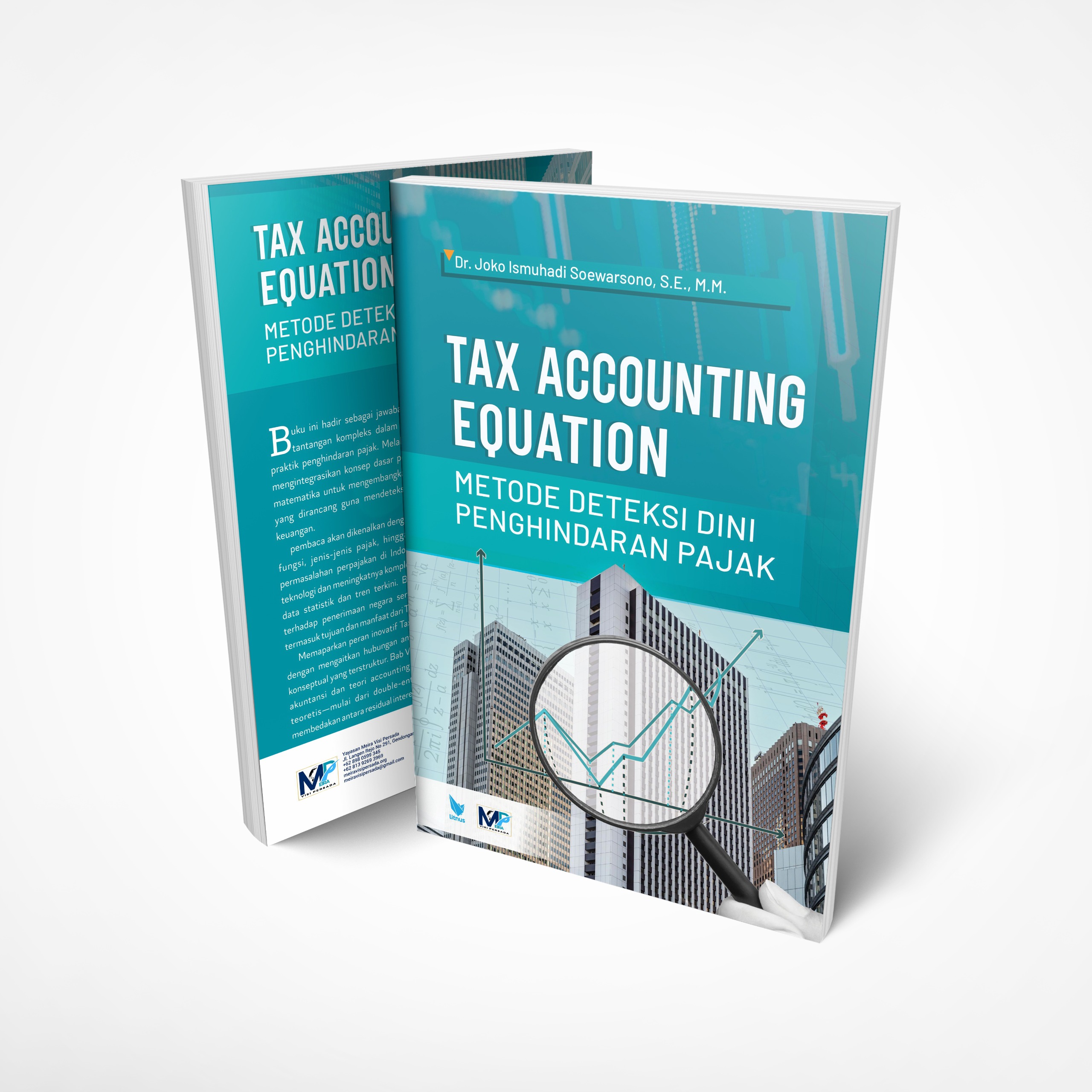
Jakarta, fiskusnews.com:
Pertanyaan yang diajukan menyoroti secara tajam potensi keterkaitan antara tindak pidana perpajakan dan delik korupsi di Indonesia, terutama dengan merujuk pada frasa “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” yang tercantum dalam Pasal 38, 39, dan 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pemikiran mengenai Pasal 44B sebagai representasi “Restorative Justice” dan Pasal 44C sebagai landasan “corporate criminal liability” dalam konteks ini juga sangat relevan. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam potensi penerapan dan tantangan konsep keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana perpajakan yang memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai korupsi, sehingga menyebabkan “kerugian pada pendapatan negara.”
Kerangka Hukum Tindak Pidana Perpajakan dan “Kerugian pada Pendapatan Negara” dalam UU KUP
Pasal 38 UU KUP: Kelalaian (Kealpaan) dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Pasal 38 UU KUP menguraikan dua bentuk utama tindak pidana perpajakan yang disebabkan oleh kelalaian (kealpaan): pertama, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan kedua, menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Meskipun tidak melibatkan unsur kesengajaan, tindakan-tindakan yang timbul akibat kelalaian ini tetap berpotensi mengakibatkan “kerugian pada pendapatan negara”. Fokus pada kealpaan mengindikasikan bahwa pelanggaran ini terjadi karena ketidakhati-hatian atau kurangnya pemahaman, bukan karena niat yang disengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan. Dalam konteks keadilan restoratif, pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian mungkin lebih mudah untuk ditangani melalui mekanisme yang menekankan pada perbaikan kesalahan dan penggantian kerugian tanpa memerlukan sanksi pidana yang berat.
Pasal 39 UU KUP: Kesengajaan (Kesengajaan) dalam Penggelapan Pajak
Pasal 39 UU KUP menjabarkan berbagai bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan dengan sengaja (kesengajaan). Tindakan-tindakan ini meliputi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP/PKP, menyalahgunakan atau menggunakan NPWP/PKP tanpa hak, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak, memperlihatkan pembukuan atau dokumen palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan dengan benar, tidak menyimpan dokumen perpajakan sesuai ketentuan, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah pasal ini, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut harus menimbulkan “kerugian pada pendapatan negara”. Adanya unsur kesengajaan dalam Pasal 39 membawa tindak pidana perpajakan lebih dekat ke ranah perbuatan yang disengaja dan berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih kompleks mengenai kesesuaian penerapan keadilan restoratif, yang mungkin perlu mempertimbangkan tidak hanya pemulihan kerugian finansial tetapi juga aspek pertanggungjawaban atas tindakan yang disengaja.
Pasal 39A UU KUP: Tindak Pidana Perpajakan Tertentu (Tindak Pidana Perpajakan Tertentu)
Pasal 39A UU KUP secara khusus menargetkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran perpajakan yang lebih berat, yaitu dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak meskipun belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelanggaran di bawah pasal ini dikenakan sanksi yang lebih berat, mencerminkan pandangan legislatif bahwa tindakan-tindakan ini merupakan bentuk penipuan pajak yang serius dan berpotensi menyebabkan “kerugian pada pendapatan negara” dalam jumlah besar. Tingkat kesengajaan dan potensi kerugian yang besar dalam pelanggaran Pasal 39A menghadirkan tantangan terbesar bagi penerapan prinsip keadilan restoratif, karena tindakan ini sering kali melibatkan perencanaan yang matang dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan merugikan negara.
Memahami Ruang Lingkup “Kerugian pada Pendapatan Negara”
“Kerugian pada pendapatan negara” dapat dipahami sebagai kekurangan dalam penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak akibat tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Istilah ini secara spesifik merujuk pada berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak dan merupakan bagian dari konsep yang lebih luas yaitu “kerugian keuangan negara”. Meskipun demikian, perhitungan “kerugian pada pendapatan negara” sering kali menggunakan jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar sebagai parameter utama. Penggunaan frasa “kerugian pada pendapatan negara” pertama kali diperkenalkan dalam UU No. 9 Tahun 1994, yang merupakan perubahan atas UU KUP sebelumnya yang menggunakan istilah “kerugian pada negara,” menunjukkan fokus yang lebih spesifik pada pendapatan dari sektor pajak. Penting untuk dicatat bahwa konsep KpPN tidak hanya mengidentifikasi jumlah pajak yang terutang, tetapi juga terkait erat dengan tindakan yang melanggar hukum perpajakan itu sendiri. Definisi yang lebih spesifik dari KpPN juga diatur dalam berbagai pasal UU KUP dan UU PBB, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
Mekanisme Penghitungan “Kerugian pada Pendapatan Negara”
Penghitungan “kerugian pada pendapatan negara” (KpPN) dilakukan dengan memperhatikan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan/atau jumlah yang seharusnya disetor ke kas negara akibat penyalahgunaan instrumen administrasi perpajakan dalam tindak pidana perpajakan. Penghitungan ini dilakukan secara terpisah untuk setiap perbuatan pidana, jenis pajak, periode pajak, dan jenis pelanggaran (materiil atau formil). Secara substansi, KpPN untuk pasal-pasal tertentu dalam UU KUP dan UU PBB memiliki definisi yang spesifik. Untuk Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU KUP, KpPN adalah jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (actual loss). Untuk Pasal 39 ayat (3) UU KUP, KpPN adalah jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan secara tidak benar. Untuk Pasal 39A UU KUP, KpPN adalah jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak sah. Sedangkan untuk Pasal 24 dan Pasal 25 UU PBB, KpPN adalah jumlah pajak yang terutang. Metode penghitungan yang rinci ini menekankan aspek finansial dari tindak pidana perpajakan dan menjadi dasar penting jika prinsip keadilan restoratif diterapkan, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara.
Memahami Keadilan Restoratif di Indonesia: Prinsip dan Aplikasi Saat Ini
Keadilan restoratif didefinisikan sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan konstruktif. Prinsip utama dari keadilan restoratif meliputi penyembuhan luka, pembelajaran moral, partisipasi komunitas, dialog, pengampunan, tanggung jawab, dan upaya untuk melakukan perubahan positif. Konsep ini secara formal diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, dasar hukum penerapan keadilan restoratif juga terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun demikian, konsep dan penerapannya masih terus berkembang dan menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Indonesia. Secara umum, penerapan keadilan restoratif di Indonesia mensyaratkan beberapa kondisi, baik materiil maupun formil. Kondisi materiil meliputi tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana, dan bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau pembunuhan. Kondisi formil meliputi adanya perdamaian dari kedua belah pihak (kecuali tindak pidana narkoba) dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Dalam peraturan Kejaksaan, terdapat persyaratan tambahan seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.5 juta. Secara keseluruhan, meskipun keadilan restoratif semakin diakui dalam sistem hukum Indonesia, penerapannya masih terbatas pada jenis-jenis tindak pidana tertentu.
Keadilan Restoratif dan Tindak Pidana Perpajakan: Analisis Konseptual
Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif pada tindak pidana perpajakan, di mana negara menjadi “korban” utama, memiliki potensi melalui mekanisme seperti pembayaran penuh kerugian negara termasuk sanksi administrasi. Pasal 44B UU KUP dapat dilihat sebagai manifestasi awal dari prinsip ini melalui pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dan pelunasan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya. Selain pemulihan kerugian finansial, keadilan restoratif dalam konteks perpajakan juga dapat mencakup komitmen dan tindakan nyata dari wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan di masa depan, seperti perbaikan sistem internal atau peningkatan pemahaman peraturan. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan ketidakjelasan interpretasi peraturan atau kesalahan administrasi yang tidak disengaja, mekanisme mediasi atau konsiliasi antara otoritas pajak dan wajib pajak juga dapat dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan kerugian negara. Meskipun konsep korban dalam tindak pidana perpajakan berbeda dengan tindak pidana konvensional, negara sebagai representasi kepentingan publik dapat dianggap sebagai pihak yang dirugikan, dan pemulihan kerugian serta peningkatan kepatuhan di masa depan dapat dipandang sebagai bentuk pemulihan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif pada Praktik Perpajakan yang Korup
Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana perpajakan yang berpotensi menjadi korupsi menghadapi tantangan yang signifikan. Korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, sering kali melibatkan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan dampak yang luas terhadap kepercayaan publik dan perekonomian. Penerapan mekanisme yang dianggap “lebih ringan” seperti keadilan restoratif dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan kurangnya efek jera. Selain itu, membuktikan unsur-unsur korupsi memerlukan proses hukum yang lebih mendalam dan pembuktian yang kuat, yang mungkin kurang memadai dalam mekanisme keadilan restoratif yang cenderung lebih cepat dan fokus pada pemulihan kerugian. Keadilan bagi masyarakat luas yang menjadi korban utama dampak korupsi juga menjadi pertimbangan penting, di mana penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tetap menjadi pilar utama. Sejumlah ahli hukum juga berpendapat bahwa keadilan restoratif tidak sesuai untuk kasus korupsi karena tidak adanya korban langsung dalam pengertian tradisional dan dampak luas korupsi terhadap masyarakat. Fokus pada pemulihan kerugian finansial mungkin tidak cukup untuk mengatasi kerusakan yang lebih luas akibat korupsi terhadap sistem dan kepercayaan publik. Beberapa ahli bahkan khawatir bahwa penerapan keadilan restoratif pada korupsi dapat disalahgunakan dan memberikan impunitas kepada pelaku. Meskipun demikian, ada pandangan yang lebih moderat yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat dipertimbangkan dalam kasus korupsi ringan atau terutama dalam hal pemulihan aset negara.
Analisis Pasal 44B UU KUP: Sebuah Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan?
Pasal 44B UU KUP menyediakan mekanisme bagi penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan demi kepentingan penerimaan negara. Pasal ini memungkinkan Jaksa Agung, atas permintaan Menteri Keuangan, untuk menghentikan penyidikan jika wajib pajak atau tersangka telah melunasi “kerugian pada pendapatan negara” beserta sanksi administrasi yang berlaku. Tingkat sanksi administrasi bervariasi tergantung pada pasal pelanggaran, yaitu satu kali jumlah kerugian untuk pelanggaran Pasal 38, tiga kali jumlah kerugian untuk pelanggaran Pasal 39, dan empat kali jumlah pajak dalam faktur pajak fiktif untuk pelanggaran Pasal 39A. Pasal 44B sering dianggap sebagai implementasi prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, di mana sanksi pidana menjadi pilihan terakhir setelah upaya administratif seperti pemulihan kerugian diutamakan. Proses pengajuan penghentian penyidikan diatur dalam PMK No. 55/PMK.03/2016 dan PMK No. 129/PMK.03/2012. Mekanisme ini bahkan dapat diterapkan pada tahap penuntutan. Pasal 44B dapat diinterpretasikan sebagai bentuk keadilan restoratif yang disesuaikan dengan konteks tindak pidana perpajakan, di mana pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama. Namun, efektivitas dan implikasi etis dari Pasal 44B masih diperdebatkan, dengan beberapa pihak khawatir bahwa pasal ini dapat mengurangi efek jera dan mengutamakan penerimaan negara di atas keadilan. Meskipun demikian, semakin banyak wajib pajak yang memanfaatkan Pasal 44B, menunjukkan relevansinya dalam penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan.
Pasal 44C UU KUP: Tanggung Jawab Pidana Korporasi dan Kaitannya dengan Keadilan Restoratif
Pasal 44C UU KUP mengatur bahwa pidana denda yang dikenakan berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang melakukan penyitaan dan pelelangan aset terpidana untuk membayar denda tersebut. Pasal ini berkaitan dengan konsep tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia, yang semakin berkembang dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun KUHP sebelumnya lebih fokus pada tanggung jawab individu, KUHP baru memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu, seperti jika korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana, jika tindakan tersebut merupakan kebijakan korporasi, atau jika korporasi gagal mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Berbagai teori tentang tanggung jawab pidana korporasi, termasuk teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability, relevan dalam konteks hukum Indonesia. PERMA No. 13 Tahun 2016 juga memberikan panduan dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 44C memperkuat akuntabilitas finansial korporasi atas tindak pidana perpajakan yang serius. Meskipun demikian, fokus pada denda mungkin lebih menekankan pada pemulihan finansial daripada aspek rehabilitatif dari keadilan restoratif.
Studi Kasus dan Perspektif Ahli tentang Keterkaitan Tindak Pidana Perpajakan dan Korupsi
Berbagai kasus di Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan erat antara tindak pidana perpajakan dan korupsi, seperti kasus Gayus Tambunan, Rafael Alun Trisambodo, dan Angin Prayitno Aji. Penggelapan pajak sering kali menjadi bagian atau modus operandi dalam skema korupsi yang lebih besar, melibatkan suap kepada petugas pajak atau penyalahgunaan wewenang. Beberapa ahli berpendapat bahwa penggelapan pajak skala besar dengan unsur kesengajaan harus diklasifikasikan sebagai korupsi karena dampaknya yang signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Namun, pandangan ahli mengenai penerapan keadilan restoratif pada kasus korupsi cenderung negatif, dengan alasan sifat kejahatan dan kurangnya korban langsung untuk rekonsiliasi. Meskipun demikian, ada juga pandangan bahwa keadilan restoratif dapat dipertimbangkan dalam kasus korupsi ringan atau untuk pemulihan aset.
| Kasus | Deskripsi Singkat | Kerugian Negara (Estimasi) | Hasil Hukum | Keadilan Restoratif |
|---|---|---|---|---|
| Gayus Tambunan | Manipulasi laporan keuangan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak, suap, dan pencucian uang. | ~Rp100 miliar | Divonis 29 tahun penjara dalam berbagai kasus. | Tidak jelas |
| Rafael Alun Trisambodo | Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan pajak dan tindak pidana pencucian uang. | ~Rp500 miliar | Divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Kasasi diajukan KPK. | Tidak jelas |
| Angin Prayitno Aji | Didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait rekayasa laporan pajak beberapa perusahaan. | ~Rp50 miliar | Divonis 7 tahun penjara dan 9 tahun penjara dalam kasus berbeda. | Tidak jelas |
| Dhana Widyatmika | Diduga menerima gratifikasi terkait utang pajak dan melakukan pemerasan serta pencucian uang. | ~Rp2.5 miliar | Divonis 10 tahun penjara setelah banding. | Tidak jelas |
| Abdul Rachman | Diduga menerima suap untuk menyetujui restitusi pajak terkait proyek jalan tol. | ~Rp1 miliar | Divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta. | Tidak jelas |
| Bahasyim Assifie | Terbukti menerima suap dari wajib pajak. | ~Rp1 miliar | Divonis 10 tahun penjara. Aset yang diduga hasil korupsi disita. | Tidak jelas |
| Tomy Hindratno | Tertangkap OTT KPK karena menerima suap terkait kasus pajak perusahaan. | ~Rp280 juta | Divonis 10 tahun penjara setelah banding. | Tidak jelas |
| Eko Darmayanto & M. Dian | Terbukti menerima suap untuk pengurusan pajak beberapa perusahaan. | Jutaan Dolar & Rupiah | Divonis 9 tahun penjara masing-masing. | Tidak jelas |
| Handang Soekarno | Tertangkap OTT KPK karena menerima suap dari Direktur perusahaan terkait pengurusan pajak. | ~Rp1.9 miliar | Divonis 10 tahun penjara. Uang yang disita ~Rp1.139 miliar. | Tidak jelas |
| Pargono Riyadi | Terbukti memeras wajib pajak dalam pengurusan pajak pribadi. | Tidak jelas | Divonis 4.5 tahun penjara. | Tidak jelas |
| Pajak Dealer Jaguar-Bentley | Empat pegawai pajak ditahan KPK karena diduga menerima suap dari komisaris perusahaan. | ~US$96.375 | Tidak ada informasi vonis dalam sumber yang diberikan. | Tidak jelas |
Kesimpulan Sementara
Menyelesaikan “extra ordinary crime” seperti korupsi murni melalui mekanisme “restorative justice” sebagaimana dipahami dalam tindak pidana ringan akan sangat sulit dan berpotensi kontraproduktif. Namun, prinsip-prinsip “restorative justice,” terutama pemulihan kerugian negara secara optimal dan perbaikan kepatuhan di masa depan, dapat diintegrasikan secara hati-hati dalam penanganan tindak pidana perpajakan, terutama pada tahap awal dan untuk kasus-kasus yang tidak secara eksplisit menunjukkan unsur korupsi yang kuat. Pasal 44B UU KUP merupakan contoh mekanisme yang mengedepankan pemulihan kerugian negara dan dapat dianggap sebagai bentuk keadilan restoratif dalam konteks perpajakan. Sementara itu, Pasal 44C memperkuat tanggung jawab pidana korporasi dalam kasus tindak pidana perpajakan yang serius. Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi tetap menjadi pilar utama dalam memberantas kejahatan luar biasa ini dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan negara secara keseluruhan. Interpretasi dan penerapan Pasal 44B, 44C, serta pasal-pasal lain dalam UU KUP harus dilakukan secara cermat dan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efek jera. Diskusi mengenai batas antara tindak pidana perpajakan biasa dan delik korupsi, serta bagaimana mekanisme penyelesaian yang tepat untuk masing-masing kategori, akan terus berkembang seiring dengan praktik penegakan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Reporter: Marshanda Gita – Pertapsi Muda
Share
Berita Lainnya
Center of Excellence: SCCR Indonesia University
Tax Accounting and the Underground Economy in Indonesia: Relevance to Recovering State Revenue Losses from Tax Crimes
Seminar Nasional: Outlook Hukum dan Ekonomi Indonesia Tahun 2025
Implementasi Komprehensif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 sebagai Fondasi Badan Penerimaan Negara: Analisis Strategis
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut Pembentukan BPN Bakal Tertunda
Rekomendasi untuk Anda
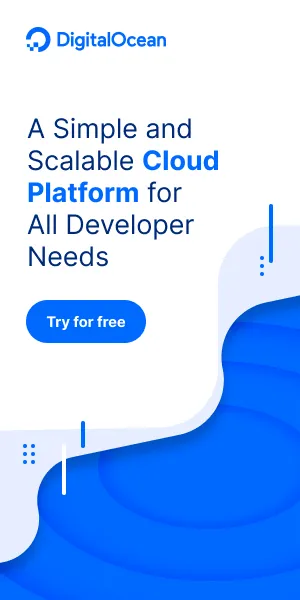
Berita Terbaru
Eksplor lebih dalam berita dan program khas fiskusnews.com
Tag Terpopuler
# #TAE
# #TAX ACCOUNTING EQUATION
# #TAX FRAUD
# #TAX EVASION